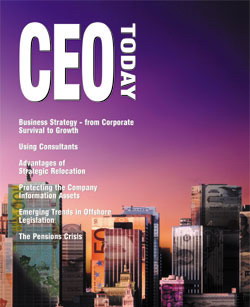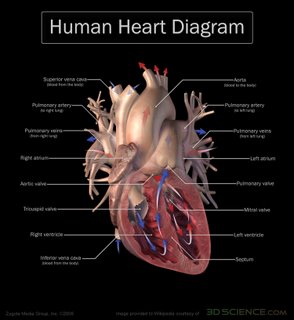Tobias, kami biasa memanggilnya. Suatu bentuk kekurangajaran mungkin kami memanggilnya demikian, karena seharusnya kami memanggilnya Kakak Tobias, mungkin karena terbiasa mendengar orang tua kami memanggilnya demikian, kami pun ikut-ikutan memanggilnya, dan tidak ada koreksi dari mereka sehingga kami selalu memanggil nama aslinya. Tentunya sekarang tidak demikian, aku pasti memanggilnya kakak Tobi kalau ketemu.
Ketika itu usiaku mungkin sekitar 3-5 tahun - tidak sepenuhnya ingat akan masa itu - tetapi berdasarkan cerita orang tua, foto-foto kami yang tersisa waktu kecil dan samar-samar ingatan ketika kecil (ini hal yang luar biasa karena kadang peristiwa masa kecil bisa terus diingat anak balita hingga dewasa), aku merasa sosok Tobias ini dekat dengan aku. Mamak cerita, ketika kecil Tobias telaten menjaga kami. Salah satu hal yang samar-samar aku ingat, orang ini suka menggendong kami, dan aku paling suka ketika digendong di pundaknya karena pada saat itu aku merasa menjadi orang besar karena tiba-tiba menjadi tinggi. Ketika itu mungkin usia Tobias belasan tahun, sekolah di SMP YPK Nabire, kota kecil di Papua, dimana 4 dari kami 5 bersaudara dilahirkan dan dibesarkan.
Tobi dan ratusan anak pedalaman Papua pada masa itu memiliki kemauan yang luar biasa untuk sekolah. Setidak-tidaknya itu yang aku pikirkan pada saat ini ketika mengingat masa itu. Hal yang lazim mendengar anak-anak dari pedalaman jalan berhari-hari ke kota yang lebih besar untuk mendapat pendidikan yang lebih lanjut, karena pendidikan lanjutan di kota asal mereka tidak ada. Biasanya di kampung mereka, mereka hanya menyelesaikan pendidikan dasar. Apabila orang tua mereka mampu, biasanya mereka akan naik pesawat Cessna, yang memiliki baling-baling tunggal. Cara mereka mendapatkan ongkos pesawat dengan menjual harta yang paling berharga yaitu babi. Di pedalaman Papua, pada masa itu nilai kekayaan diukur dengan jumlah babi yang dimiliki seseorang.
Mereka tidak memikirkan bagaimana cara mereka akan menyambung hidup di kota besar (tidak lebih besar dari sebuah dusun di pulau Jawa) Papua nantinya. Yang penting pergi ke kota, daftar sekolah, selanjutnya untuk bertahan hidup urusan nanti. Ketika pertama kali datang ke kota yang lebih besar, kebanyakan dari mereka berkumpul dalam komunitas mereka. Rasa sosialnya luar biasa, "one for all and all for one". Ketika berkumpul dalam komunitas mereka kebanyakan berkebun dengan menanam umbi-umbian dan memelihara babi.
Sebagian kecil dari mereka (seperti Tobias), biasanya menjadi anak angkat keluarga pendatang di Papua. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, membersihkan halaman,dll. Biasanya yang seperti ini hidupnya lebih teratur dibandingkan mereka yang berkumpul bersama-sama dalam komunitas mereka.
Didalam keterbatasan, kesederhanaan,keluguan dan keyakinan akan pendidikan yang mampu merubah masa depan menjadi lebih baik, anak-anak Papua ini memperbaiki kualitas hidup mereka. Meski mereka masih hidup dalam jaman batu, dengan alur pemikiran yang sederhana, sungguh luar biasa kalo dipikir saat ini, kemauan mereka untuk mendapat pendidikan yang lebih baik. Jumlahnya bukan satu atau dua, tetapi ratusan bahkan ribuan. Sayang sistem pendidikan kita tidak didesain lebih baik untuk mengakomodir kebutuhan anak-anak di Papua akan pendidikan, karena terus terang kualitas pendidikan di sana sangat rendah dibandingkan saudara-saudara mereka di Pulau Sulawesi, Sumatera apalagi Jawa, tetapi bicara tentang keinginan untuk maju, anak-anak Papua patut diacungi jempol !!!
Ale dan Nia, mencoba menceritakan salah satu dari anak-anak Papua yang berhasil mewujudkan keinginannya untuk mendapat pendidikan yang lebih maju : "Denias". Film yang mengajak kita untuk menghargai pendidikan dan memberi apresiasi buat mereka yang berjuang untuk lebih maju dan lebih baik dari sebelumnya. Ini tidak hanya terjadi di Hollywood, tetapi bisa juga di pedalaman Papua... Terima kasih Ale dan Nia karena kalian mengingatkan kami, bahwa anak-anak Papua juga ingin mendapat pendidikan yang lebih baik.